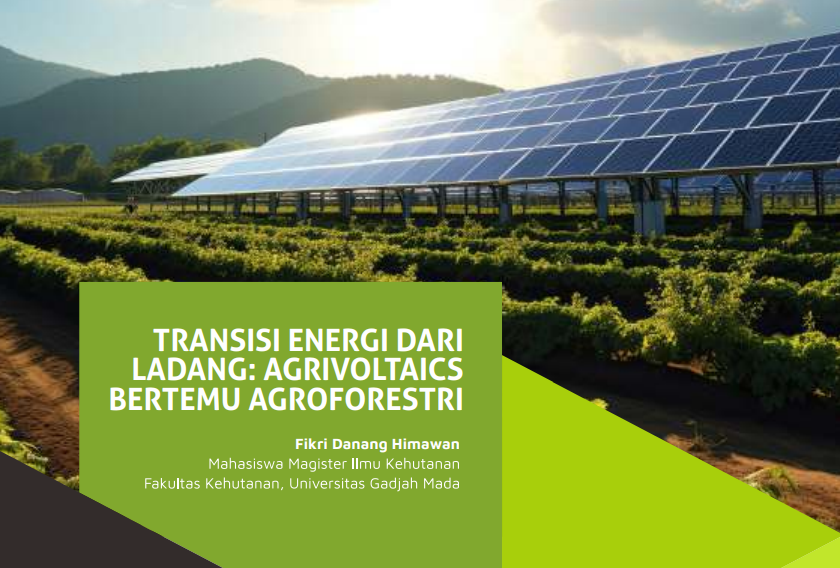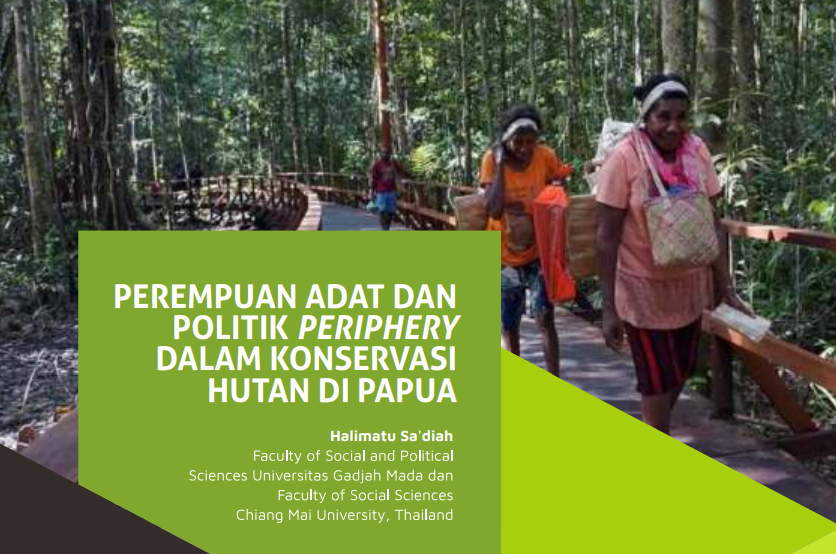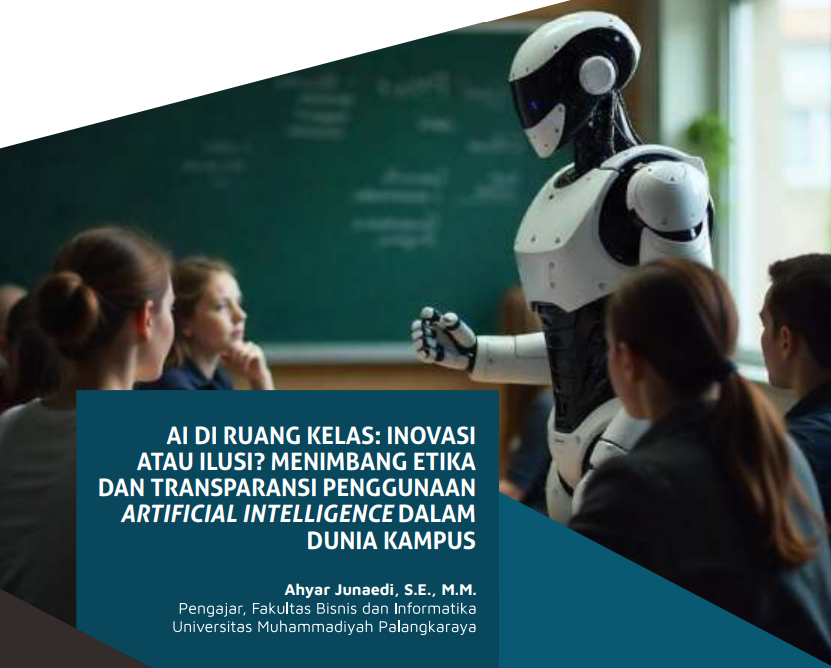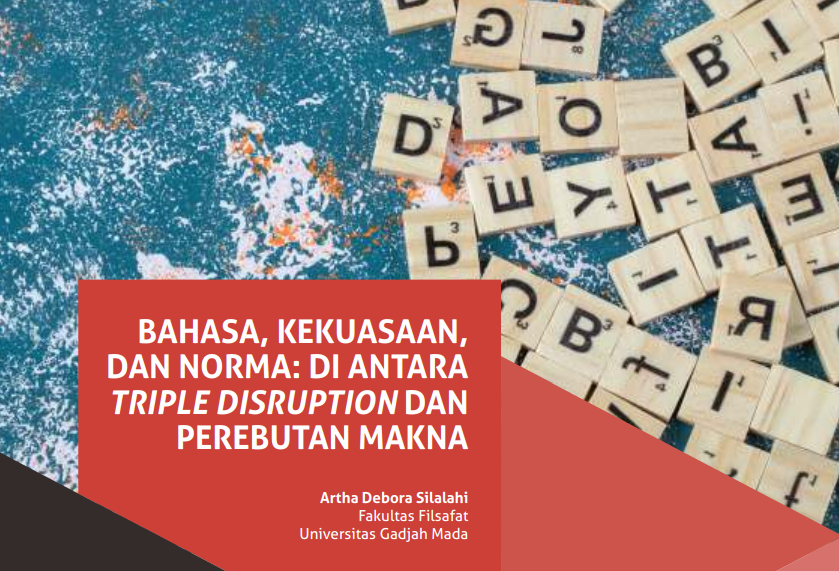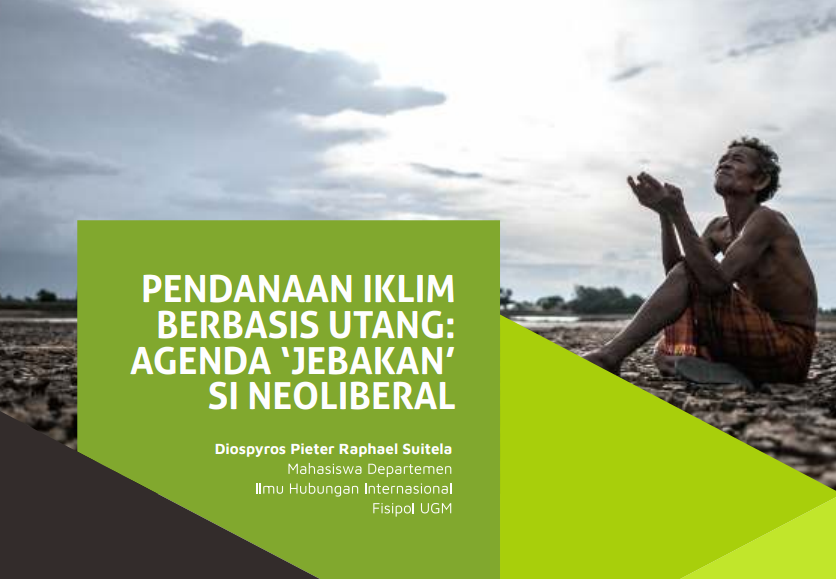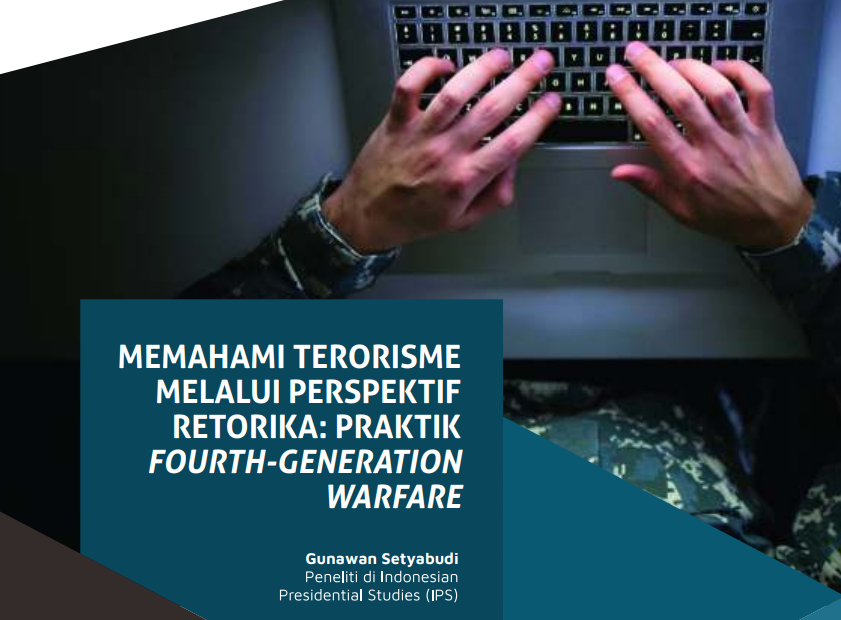E-Governance telah menjadi instrumen utama modernisasi tata kelola negara dengan memanfaatkan teknologi digital untuk memperkuat transparansi, akuntabilitas, dan efisiensi birokrasi, sembari menjamin hak warga atas informasi serta partisipasi publik. Regulasi nasional maupun internasional mendorong keterbukaan data, sementara Memorandum of Understanding (MoU) berfungsi sebagai instrumen tata kelola kolaboratif yang mencerminkan pergeseran dari model birokratis hirarkis menuju governance berbasis jejaring. Heywood (2014) menyebut fenomena ini sebagai bagian dari “perancangan kembali” pemerintahan, di mana negara tidak lagi semata penyedia layanan langsung, melainkan fasilitator yang memberdayakan masyarakat atau menetapkan aturan umum. Namun, modernisasi yang cepat, responsif dan efisien ini menimbulkan pertanyaan mendasar: apakah keterbukaan digital sungguh menjamin transparansi substantif, atau justru menciptakan ilusi partisipatif? Apakah MoU menjadi instrumen demokratisasi atau sekadar legitimasi kekuasaan?
Wigke Capri
Tren digital yang mendominasi konsumsi publik hari ini adalah konten komedi satire atau juga disebut ‘tepi jurang’. Fenomena ini muncul dari tiga pemicu krusial: kemudahan mengakses fitur media sosial, maraknya stand-up comedy di Indonesia, dan pembatasan ekspresi dalam UU ITE. Kombinasi inilah yang mendorong maraknya kritik tersirat terhadap pemerintah dan aktor politik melalui komedi satire.
Dalam melihat tren ini, perlu menggarisbawahi bagaimana ruang publik digital memainkan peran penting dalam partisipasi politik publik. Teknologi primer dan partisipasi politik menunjukkan hubungan yang kuat di antara keduanya (Buchstein, 1997). Dalam ruang publik digital masyarakat mendapatkan ruang untuk berekspresi dengan melontarkan kreativitas, ide, gagasan, dan kritik. Kehadiran internet dan media sosial menyediakan aksesibilitas untuk menghubungkan orang-orang dari berbagai latar belakang untuk menyalurkan wacana, ekspresi, serta terlibat diskusi pada ranah sosial dan politik (Papacharissi, 2002).
Bagaimana jika satu hektare tanah bisa menumbuhkan pangan, menghasilkan listrik, dan sekaligus menyelamatkan bumi?
Imajinasikan sebuah lahan pertanian yang ada di pedesaan terpasang panel surya yang diintegrasikan dengan pepohonan dan jahe, cabai, terong, atau bahkan kopi. Sinar matahari umumnya digunakan secara terpisah untuk pertanian dan panel surya, kini dapat digunakan secara bersamaan dalam satu sistem yang disebut agrivoltaics. Konsep ini bukan utopis, tapi merupakan solusi canggih yang mulai diuji dan diterapkan di berbagai negara.
Mencari alternatif di tengah logika ekonomi yang dominan bukanlah perkara mudah. Perspektif pengelolaan sumber daya alam negara haruslah mengedepankan cara-cara lokal yang telah tertanam dengan lingkungan masyarakat yang selama ini hanya dipandang sebagai keterbelakangan. Sebenarnya, budaya kearifan lokal ini menjadi pembeda dari masifnya perkembangan modern yang ada. Hanya saja narasi yang digunakan dalam memandang pengetahuan dan kearifan lokal sebagai suatu hal yang harus dihilangkan dan diganti menjadi budaya modern.
Perebutan kepemilikan atas hutan masih terjadi di Indonesia. Pemerintah gagal membangun mekanisme pengawasan yang partisipatif, terutama dalam melindungi hak masyarakat adat, termasuk perempuan yang kehilangan akses terhadap sumber daya penghidupan (Savirani, 2018). Perempuan adat dihadapkan pada tanggung jawab dalam konservasi hutan, di samping itu mereka juga menjadi korban ketika akses mereka ke sistem penyangga kehidupan terputus. Berdasarkan data gabungan dari Global Forest Watch dan Badan Pusat Statistik (BPS), sekitar 10-15% dari total deforestasi di Indonesia telah diubah menjadi kawasan industri, perkebunan, dan infrastruktur selama satu dekade terakhir. Seperti di Papua, banyak hutan telah beralih fungsi karena kepentingan pihak-pihak swasta. United Nations Programme on Reducing Emissions from Deforestation and Forest Degradation (UN-REDD Programme) mencatat sekitar 115.459 hektar kawasan hutan hilang pada tahun 2020. Hal ini menunjukkan kegagalan pemerintah dalam dua hal: (1) mengabaikan peran perempuan adat dalam konservasi hutan, (2) mempertahankan sentralisasi kekuasaan sehingga kebijakan kerap tidak sesuai dengan kebutuhan daerah.
Artificial Intelligence (AI) terus berkembang. Teknologi ini mulai digunakan di kampus di seluruh dunia untuk berbagai hal, seperti membuat materi kuliah, membuat soal evaluasi, dan menilai tugas mahasiswa. Apakah, bagaimanapun, adopsi AI di ruang kelas merupakan kemajuan? Apakah benar-benar menciptakan perbedaan moral baru antara pendidik dan siswa?
Northeastern University di Massachusetts, Amerika Serikat, memiliki kasus yang menarik. Seorang siswa bernama Ella Stapleton menuntut pengembalian uang kuliah sebesar $8.000 setelah mengetahui bahwa gurunya menggunakan ChatGPT untuk membuat materi pelajaran (Desk, 2025). Ironisnya, siswa dilarang menggunakan AI untuk menyelesaikan tugas di kelas yang sama. Stapleton menggambarkan ini sebagai jenis “kemunafikan institusional” yang merusak kredibilitas dan kejujuran pendidikan tinggi.
Indonesia berada dalam pusaran Triple Disruption mencakup disrupsi teknologi, ekologi, dan sosial-politik. Ketiga guncangan ini bukan hanya mengguncang fondasi ekonomi dan lingkungan, tetapi juga memaksa kita mempertanyakan ulang tatanan kekuasaan dan cara kita memahami makna, hukum, dan hidup bernegara. Dalam pusaran ini, bahasa menjadi lebih dari sekadar alat komunikasi. Ia berubah menjadi arena politik, senjata ideologis, dan alat legitimasi. Bahasa menjadi pengatur makna yang menentukan siapa yang berkuasa dan siapa yang dikecualikan dari wacana publik. Manusia tidak dapat dilepaskan dari dimensi kebahasaan (Gadamer, 1985). Seperti yang diungkapkan Gadamer, hubungan manusia dengan dunia terjadi lewat bahasa. Dalam pusaran Triple Disruption ini, penting untuk memahami bagaimana bahasa bekerja sebagai instrumen kekuasaan dalam konteks disrupsi teknologi, ekologi, dan sosial-politik.
Ketika negara berkembang dipaksa meminjam uang untuk menyelamatkan planet yang rusak, coba pikir kembali: bantuan atau jebakan?
Bumi sedang terbakar! Pertanggungjawaban terhadap krisis iklim menjadi bahasan pokok dalam Conference of the Parties (COP) untuk salah satunya membicarakan skema pendanaan iklim. Pada awalnya, skema pendanaan ini ditujukan untuk untuk membantu berbagai program adaptasi dan mitigasi iklim di negara-negara berkembang melalui skema utang luar negeri (OECD, 2010). Kendati demikian, skema pendanaan iklim berbasis utang justru mengekspresikan logika neoliberal yang mengalihkan kekuasaan kepada para pelaku pasar, juga menciptakan kondisi yang sangat merugikan negara berkembang untuk semakin terpuruk dalam krisis ekonomi, alih-alih beradaptasi dengan cepat dalam menghadapi krisis iklim (Bracking & Leffel, 2021). Dengan berkaca pada hegemoni yang didefinisikan oleh Gramsci, tulisan ini dipandu oleh 1 (satu) pertanyaan: bagaimana pendanaan iklim berbasis utang merupakan instrumen hegemonisasi neoliberal dalam tatanan global?
Saat ini, media digital telah memfasilitasi kebutuhan kontemporer masyarakat global. Kita harus mengatakan bahwa media digital telah memberikan kemudahan dalam mengakses informasi dan berkomunikasi. Namun, media digital juga menimbulkan resiko baru terkait penggunaannya oleh kelompok teroris guna mendiseminasikan ideologi dan merekrut anggota. Fakta memperlihatkan remaja di negara eropa dan asia yang banyak menghabiskan waktu di dunia virtual lebih mudah teradikalisasi dan bergabung ke dalam kelompok teroris (Bastug, et al, 2018 & Nuraniyah, 2018). Perkembangan jaringan teroris semakin luas sejak pandemi COVID-19, sebab masyarakat global banyak menghabiskan waktu di dunia virtual (Basit, 2020). Paparan digital ini dilihat kelompok teroris sebagai peluang untuk mengintensifkan pesan persuasi guna meradikalisasi dan merekrut anggota baru. Oleh sebab itu, tulisan ini menjelaskan bagaimana kelompok teroris menggunakan media digital untuk memperluas jaringannya.
Dalam rapat kerja dengan Komisi IX DPR RI pada 13 November 2024, Menteri Keuangan Sri Mulyani menekankan pentingnya industri berorientasi ekspor untuk mencapai target pertumbuhan ekonomi delapan persen (Nugroho, 2024). Namun, penulis melihat bahwa pemerintah juga perlu mengintensifkan ekspor jasa mengingat kondisi perdagangan global yang semakin proteksionis, terutama dengan terpilihnya kembali Donald Trump sebagai Presiden Amerika Serikat. Penjualan jasa digital semakin menjanjikan berkat kemajuan teknologi yang memberi peluang bagi masyarakat untuk dapat mengakses pasar yang lebih mengglobal (Winanti et al., 2021: 17).