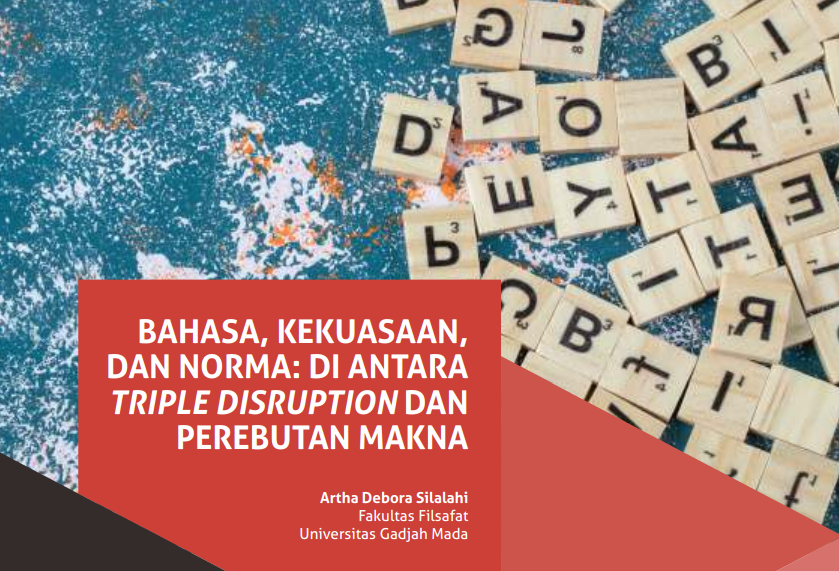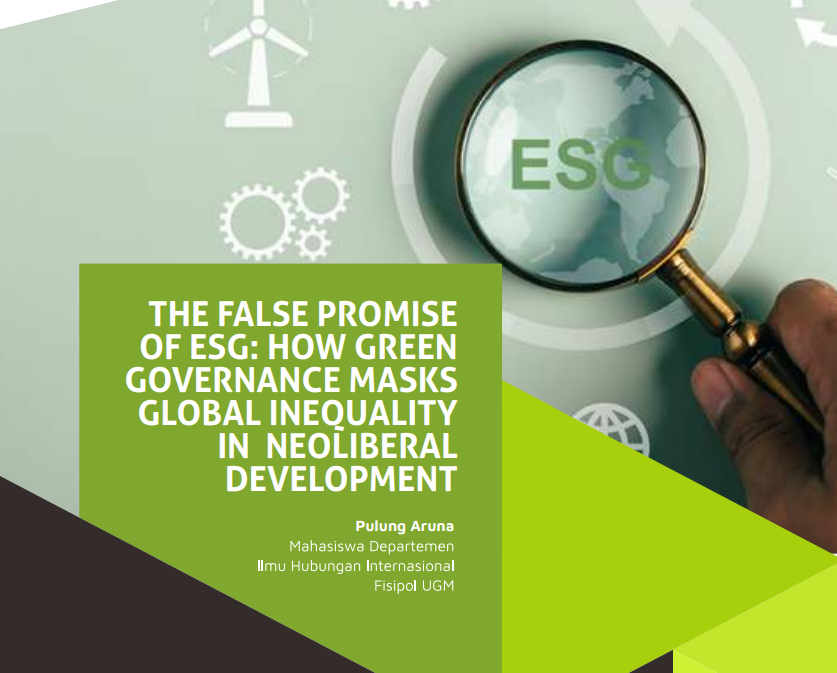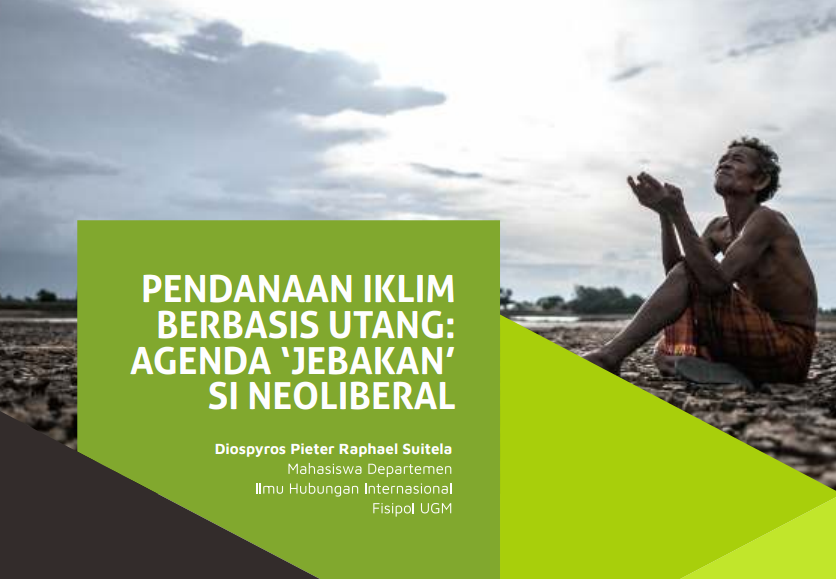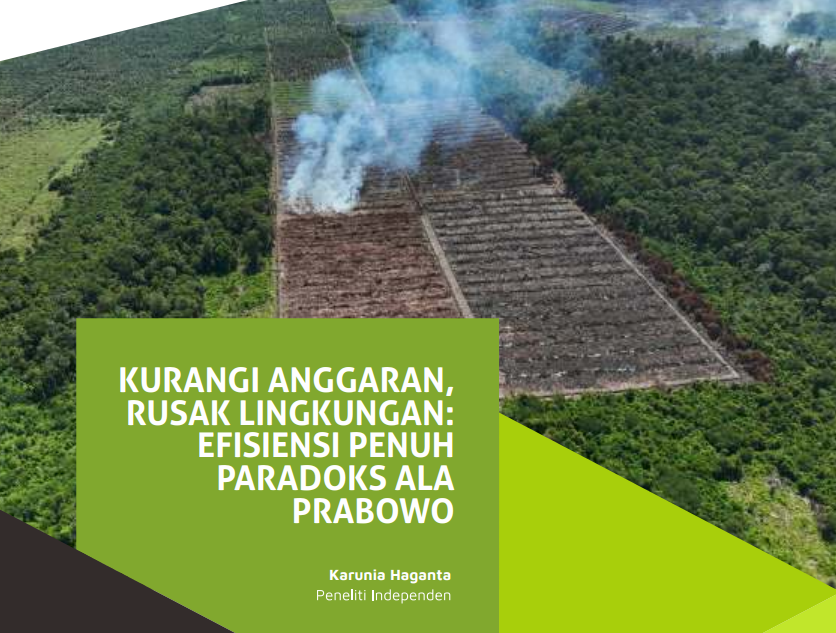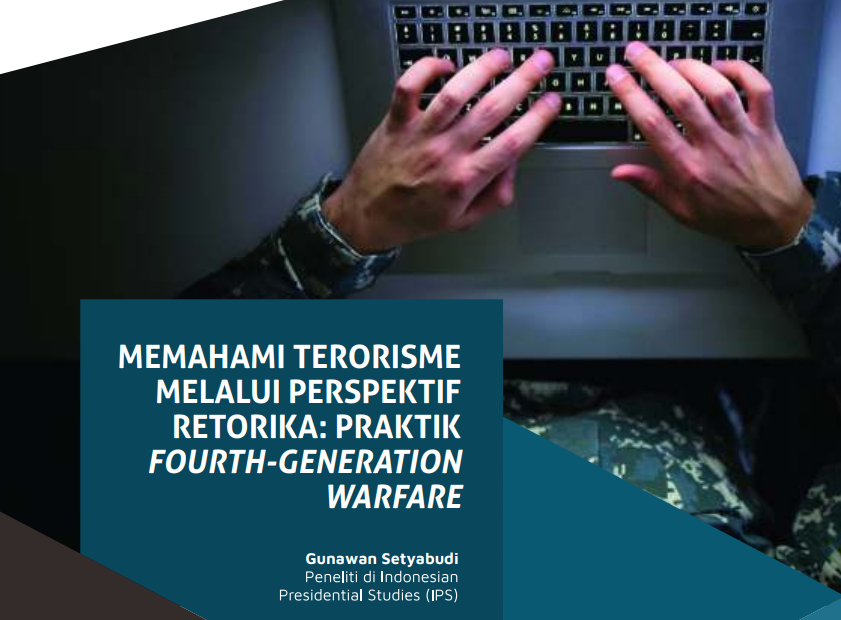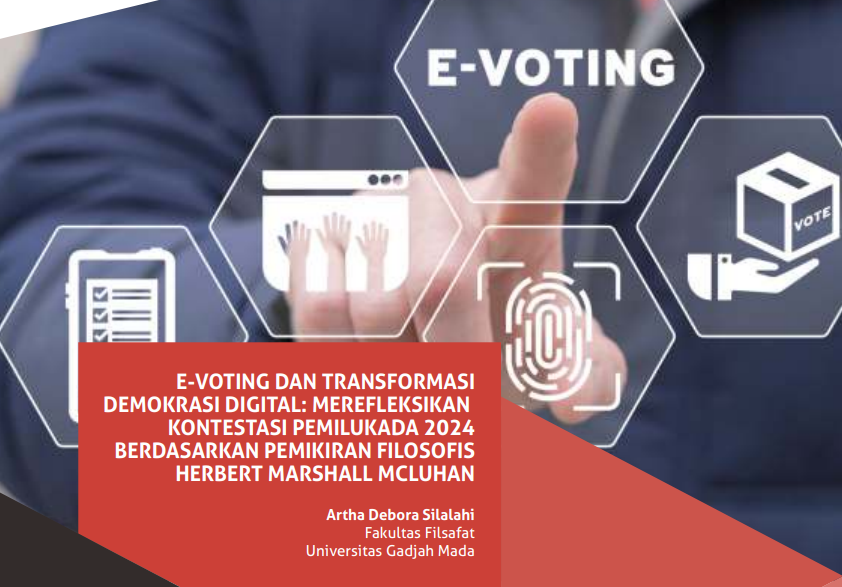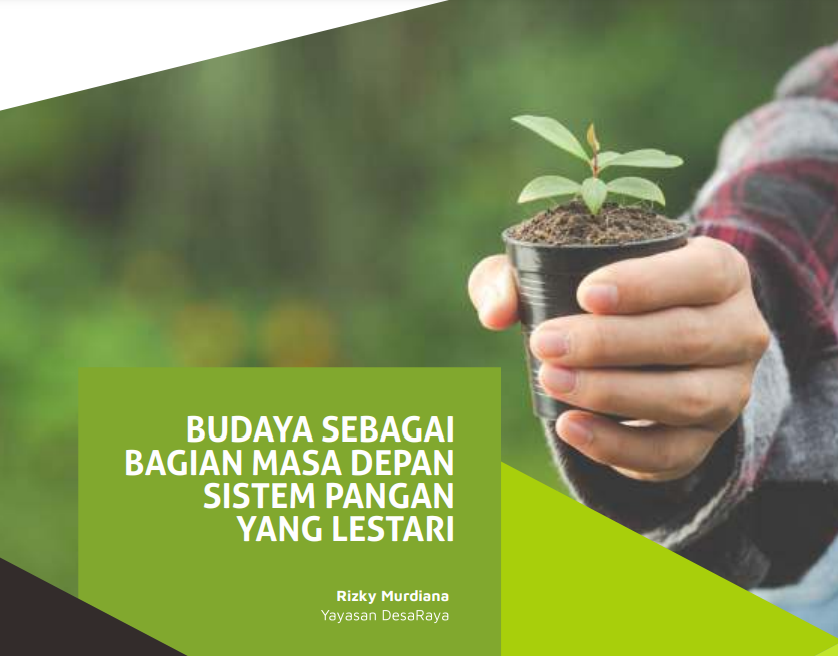Indonesia berada dalam pusaran Triple Disruption mencakup disrupsi teknologi, ekologi, dan sosial-politik. Ketiga guncangan ini bukan hanya mengguncang fondasi ekonomi dan lingkungan, tetapi juga memaksa kita mempertanyakan ulang tatanan kekuasaan dan cara kita memahami makna, hukum, dan hidup bernegara. Dalam pusaran ini, bahasa menjadi lebih dari sekadar alat komunikasi. Ia berubah menjadi arena politik, senjata ideologis, dan alat legitimasi. Bahasa menjadi pengatur makna yang menentukan siapa yang berkuasa dan siapa yang dikecualikan dari wacana publik. Manusia tidak dapat dilepaskan dari dimensi kebahasaan (Gadamer, 1985). Seperti yang diungkapkan Gadamer, hubungan manusia dengan dunia terjadi lewat bahasa. Dalam pusaran Triple Disruption ini, penting untuk memahami bagaimana bahasa bekerja sebagai instrumen kekuasaan dalam konteks disrupsi teknologi, ekologi, dan sosial-politik.
brief article
Over the course of the past ten years, the Environmental, Social and Governance (ESG) framework has become the primary instrument employed by global corporate bodies and international financial institutions in various ways to transition to a sustainable economy. ESG is promoted as the practical, if not cynical, answer to social inequality and the climate crisis, the intellectual fix for capitalism whereby social change is engineered via the mechanisms of financial markets. On the whole, however, in contrast to this rosy perspective, ESG represents the new face of green neoliberalism, a mode of capitalism that uses sustainability covers to sustain market dominance and stabilize the unequal global economic order.
Ketika negara berkembang dipaksa meminjam uang untuk menyelamatkan planet yang rusak, coba pikir kembali: bantuan atau jebakan?
Bumi sedang terbakar! Pertanggungjawaban terhadap krisis iklim menjadi bahasan pokok dalam Conference of the Parties (COP) untuk salah satunya membicarakan skema pendanaan iklim. Pada awalnya, skema pendanaan ini ditujukan untuk untuk membantu berbagai program adaptasi dan mitigasi iklim di negara-negara berkembang melalui skema utang luar negeri (OECD, 2010). Kendati demikian, skema pendanaan iklim berbasis utang justru mengekspresikan logika neoliberal yang mengalihkan kekuasaan kepada para pelaku pasar, juga menciptakan kondisi yang sangat merugikan negara berkembang untuk semakin terpuruk dalam krisis ekonomi, alih-alih beradaptasi dengan cepat dalam menghadapi krisis iklim (Bracking & Leffel, 2021). Dengan berkaca pada hegemoni yang didefinisikan oleh Gramsci, tulisan ini dipandu oleh 1 (satu) pertanyaan: bagaimana pendanaan iklim berbasis utang merupakan instrumen hegemonisasi neoliberal dalam tatanan global?
Awal 2025, pemerintahan baru Prabowo Subianto telah membuat gebrakan baru dengan melakukan pemotongan anggaran besar-besaran. Kebijakan yang disebutnya “efisiensi” ini secara masif mengurangi anggaran berbagai lembaga negara yang dianggap pemborosan. Banyak yang mengeluhkan dampak langsung efisiensi ini, mulai dari pemecatan terhadap banyak tenaga honorer yang kerap berada di garis depan pelayanan, penurunan fasilitas kerja, sampai ancaman dihentikannya program-program bantuan pendidikan.
Namun, kritik terbesar bagi efisiensi ini sesungguhnya adalah kontradiksi pemerintahan Prabowo. Sejak awal, Prabowo membentuk kabinet yang dianggap tidak proporsional dengan banyaknya posisi dan jabatan yang diberikan (Sood, 2024). Kontradiksi ini makin terlihat dengan rencana Prabowo untuk mengalihkan dana pada program kontroversial Makan Bergizi Gratis (MBG), dan yang terbaru adalah lembaga kontroversial Danantara (Siswanto, 2025).
Saat ini, media digital telah memfasilitasi kebutuhan kontemporer masyarakat global. Kita harus mengatakan bahwa media digital telah memberikan kemudahan dalam mengakses informasi dan berkomunikasi. Namun, media digital juga menimbulkan resiko baru terkait penggunaannya oleh kelompok teroris guna mendiseminasikan ideologi dan merekrut anggota. Fakta memperlihatkan remaja di negara eropa dan asia yang banyak menghabiskan waktu di dunia virtual lebih mudah teradikalisasi dan bergabung ke dalam kelompok teroris (Bastug, et al, 2018 & Nuraniyah, 2018). Perkembangan jaringan teroris semakin luas sejak pandemi COVID-19, sebab masyarakat global banyak menghabiskan waktu di dunia virtual (Basit, 2020). Paparan digital ini dilihat kelompok teroris sebagai peluang untuk mengintensifkan pesan persuasi guna meradikalisasi dan merekrut anggota baru. Oleh sebab itu, tulisan ini menjelaskan bagaimana kelompok teroris menggunakan media digital untuk memperluas jaringannya.
Dalam rapat kerja dengan Komisi IX DPR RI pada 13 November 2024, Menteri Keuangan Sri Mulyani menekankan pentingnya industri berorientasi ekspor untuk mencapai target pertumbuhan ekonomi delapan persen (Nugroho, 2024). Namun, penulis melihat bahwa pemerintah juga perlu mengintensifkan ekspor jasa mengingat kondisi perdagangan global yang semakin proteksionis, terutama dengan terpilihnya kembali Donald Trump sebagai Presiden Amerika Serikat. Penjualan jasa digital semakin menjanjikan berkat kemajuan teknologi yang memberi peluang bagi masyarakat untuk dapat mengakses pasar yang lebih mengglobal (Winanti et al., 2021: 17).
In the midst of the climate crisis, the role of religious organizations is increasingly crucial. Islamic religious organizations as the majority religion in Indonesia promote Green Islam (Jannah, 2024) as their commitment to the issue. However, this commitment is questioned by the ambivalent attitude of these religious organizations towards the climate crisis, especially because of the closeness of religious organizations with the government through the submission of Mining Licenses (IUP) to religious organizations such as NU and Muhammadiyah.
[av_textblock fold_type=” fold_height=” fold_more=’Read more’ fold_less=’Read less’ fold_text_style=” fold_btn_align=” textblock_styling_align=” textblock_styling=” textblock_styling_gap=” textblock_styling_mobile=” size=” av-desktop-font-size=” av-medium-font-size=” av-small-font-size=” av-mini-font-size=” font_color=” color=” fold_overlay_color=” fold_text_color=” fold_btn_color=’theme-color’ fold_btn_bg_color=” fold_btn_font_color=” size-btn-text=” av-desktop-font-size-btn-text=” av-medium-font-size-btn-text=” av-small-font-size-btn-text=” av-mini-font-size-btn-text=” fold_timer=” z_index_fold=” id=” custom_class=” template_class=” element_template=” one_element_template=” av_uid=’av-m60gmajn’ sc_version=’1.0′ admin_preview_bg=”]
Online Complaint Handling System atau mekanisme penanganan keluhan merupakan sistem yang dirancang secara daring (digital) untuk menangani keluhan atau pengaduan dari masyarakat atas layanan yang mereka terima. Sistem ini bertujuan untuk memastikan bahwa suara warga didengar, masalah mereka diselesaikan, dan penyedia layanan bertanggung jawab atas kualitas serta keamanan layanan yang diberikan. Menurut Mees dan Driessen (2019) sistem penanganan keluhan memiliki lima elemen utama: tanggung jawab dan mandat yang jelas, transparansi, pengawasan politik, kontrol warga, serta pemeriksaan dan sanksi, yang bergantung pada partisipasi masyarakat untuk memastikan penyedia layanan bertanggung jawab atas kualitas dan keamanan layanan. Pada prosesnya mekanisme ini juga harus transparan, responsif, dan mudah diakses oleh seluruh lapisan masyarakat.
Transformasi digital telah menjadi bagian tak terpisahkan dari kehidupan modern, termasuk dalam ranah demokrasi dan pemilu. Pemilu sebagai salah satu pilar demokrasi kini mengalami perubahan signifikan dengan adopsi teknologi digital, yang menawarkan efisiensi dan kemudahan partisipasi, terutama melalui inovasi E-Voting. Di Indonesia, dengan luasnya wilayah geografis dan kompleksitas logistik dalam penyelenggaraan Pemilukada, penerapan E-Voting dapat dijadikan sebagai solusi potensial. Pemilukada 2024 menghadirkan momentum penting untuk menilai bagaimana teknologi digital dapat diintegrasikan ke dalam sistem pemilu Indonesia. Namun, di balik potensi yang besar, E-Voting juga membawa tantangan. Ketergantungan pada teknologi memunculkan isu kritis seperti kesenjangan akses digital, keamanan siber, perlindungan privasi, dan transparansi proses pemilu. Semua ini menuntut refleksi mendalam, tidak hanya dari sudut pandang teknis tetapi juga dari perspektif filosofis. Herbert Marshall McLuhan (1911-1980) atau yang dikenal dengan nama McLuhan, seorang filsuf media terkemuka, memberikan kerangka berpikir yang relevan untuk memahami teknologi sebagai media yang tidak hanya berfungsi sebagai alat, tetapi juga menciptakan dampak mendalam pada struktur sosial, pola pikir, dan proses pertahanan diri manusia dalam menaklukkan keterbatasan tubuh manusia (McLuhan, 1964). Teknologi direproduksi oleh manusia sebagai perluasan tubuh manusia yang berada di luar dirinya dan dikenal sebagai media. Manusia secara sadar harus dapat memahami proses lahirnya teknologi secara sadar untuk menjadikan dirinya tidak hanya sebagai alat reproduksi teknologi semata tetapi yang dapat memahami reproduksi teknologi sebagai tindakan aktif perluasan dirinya yang senantiasa berada dalam kesatuan dengan dimensi interioritasnya.
Menghadapi tantangan bonus demografi dan perubahan iklim, persoalan tentang pangan menjadi urusan vital di Indonesia. Penulis mencermati terdapat empat masalah kronis pangan di Indonesia. Pertama, pangan selalu dikaitkan dengan urusan produksi, mengabaikan unsur budaya. Padahal, ketika merujuk pada studi Altieri (2004) diketahui bahwa budaya seharusnya membentuk bagaimana suatu pangan diproduksi. Budaya yang dimaksud di sini didefinisikan sebagai sebuah makna dan sistem yang unik, dibagikan oleh suatu kelompok dan ditransmisikan lintas generasi, yang memungkinkan kelompok tersebut memenuhi kebutuhan dasar untuk bertahan hidup (Alonso, Cockx, & Swinnen, 2018). Penulis menilai, keterkaitan antara urusan pangan dan budaya dapat dilihat dari pelaksanaan proyek food estate dari pemerintah. Sebagai contoh dalam kasus Papua, komunitas lokal disana dicerabut dari kebiasaan turun temurunnya yang mengonsumsi sagu dan pangan lokal. Saat ini, masyarakat lokal papua mengalami ketergantungan pada nasi dan pangan instant untuk memenuhi kebutuhan nutrisi (Krisandi & Wijanarko, 2024).