Cancel Culture, Bola Api Liar Kebebasan Bersuara Di Era Virtual
Memantau lini masa Twitter sambil menyeruput es kopi di siang bolong memanglah nikmat. Apalagi ditemani alunan musik dari musisi yang anda idolakan sejak lama. Namun, pernahkah anda merasakan situasi itu seketika berubah dalam hitungan menit, ketika berhembus kabar bahwa musisi yang anda idamkan itu terkena cancel oleh warganet? Ratusan opini kontra bertubi-tubi memenuhi lini masa yang anda ikuti. Hal ini membuat anda bingung, dan bahkan terkonstruksi untuk ikut memboikot idola anda meski belum ada klarifiksasi yang jelas. Jika anda pernah berada di posisi ini, maka anda sudah menjadi bagian dari wacana cancel culture atau budaya pengenyahan, situasi di mana anda menarik rasa simpati dan empati dari seseorang atas tindakan yang disematkan kepadanya, hingga tidak jarang berujung pengucilan.
Dalam studi Saint-Louis (2021) “Understanding Cancel Culture: Normative and Unequal Sanctioning” mengatakan bahwa cancel culture telah menjadi fenomena menarik di era virtual. Warganet akan menandai dan mengucilkan individu yang melanggar norma di media sosial. Sebagai contoh yang dialami novelis kawakan, JK Rowling pada Desember tahun 2019 lalu. Seperti dikutip dari nbcnews.com bahwa penulis fiksi Harry Potter ini di-cancel oleh para warganet karena menunjukkan dukungannya pada peneliti dengan pandangan “transphobic”. JK Rowling yang memiliki pengikut lebih dari 14 Juta di platform Twitter ini pun dihujat karena dituduh ikut menyuarakan sikap transfobia.
Di Indonesia, fenomena Call out atau canceled juga tidak bisa ditepis. Seperti pada kasus tuduhan pelecehan seksual yang dialamatkan kepada Youtuber kawakan, Gofar Hilman, yang hingga kini seperti yang dikutip pramborsfm.com, belum ada keterangan lanjutan dari kasus tersebut. Contoh lain misalnya, drummer band pop punk Superman is Dead, Jerinx, yang secara tegas menolak Covid-19 sebagai pandemi yang nyata dan merupakan konspirasi elit politik semata. Meski kemudian dirinya berujung pada kasus hukum akibat pencemaran nama baik seperti yang dikutip cnnindonesia.com. Serbuan komentar warganet ramai memboikot public figure ini dengan alasan yang tentu saja berseberangan dengan apa yang publik asumsikan, meski pembelaan diri telah dilakukan sebelumnya.
Lebih lanjut, meski jumlah kasus-kasus yang menimpa selebritas ataupun influencer lainnya tidak sedikit, budaya cancelling cukup menjadi bukti kuat bahwa siapa saja dapat menjadi target. Cancel culture menghadirkan dinamika perdebatan seperti dua sisi mata koin. Kasus yang menimpa JK Rowling, Gofar Hilman, Jerinx, dan lain sebagianya, dapat dilihat dalam kacamata budaya pengenyahan sebagai fenomena di mana dapat mendorong banyak orang untuk mempromosikan pemboikotan terhadap orang, perusahaan, dan sistem yang berbeda karena ketidakselarasan dengan nilai-nilai sosial. Cancelling people dapat disalahgunakan dengan kuat, tetapi juga mampu menyoroti ketidakadilan yang telah dipendam sebegitu lama.
Studi Sailofsky (2021) “Masculinity, Cancel Culture and Woke Capitalism: Exploring Twitter Response to Brendan Leipsic’s Leaked Conversation” menyebutkan budaya pengenyahan ini sebagai bagian yang betanggung jawab atas hilangnya reputasi tokoh-tokoh selebritas yang tidak pernah secara resmi dihukum karena pelanggaran pidana. Dalam menilik budaya pengenyahan ini, teori spiral of silence dari Neumann (1974) selayaknya mampu membedah bagaimana sosial media memiliki peran penting dalam membingkai isu dan membungkam orang-orang yang memiliki suara yang minor.
Teori Spiral of Silence Elisabeth Noelle-Neumann
Elisabeth Noelle-Neumann, seorang ahli politik dan komunikasi massa asal Jerman menjelaskan teori spiral of silence sebagai pisau analisis bagaimana komunikasi interpersonal dan media beroperasi bersama dalam pengembangan opini publik. Mengacu pada teori ini, persepsi menjadi mayoritas atau minoritas dalam opini di kelompok mana pun memengaruhi proses komunikasi interpersonal, terutama ekspresi terbuka dari sikap dan keyakinan tentang masalah moral yang sangat terpolarisasi.
Teori spiral of silence melihat individu yang merasa opininya kalah dari opini populer akan cenderung diam. Dan hal ini terjadi secara spiral, di mana opini populer terus diproduksi dan opini yang minor sangat sedikit atau bahkan tidak mendapat tempat sama sekali. Pro-kontra terhadap budaya pengenyahan ini di ruang publik, baik di ruang non-virtual ataupun virtual, menunjukkan kekhawatiran bahwa kebrutalan warganet mungkin tidak sebanding dengan pelanggaran aslinya.
Sudut pandang lainnya dapat dilihat dalam riset Bouvier (2020) “Racist Call-outs and Cancel Culture on Twitter: The Limitations of the Platform’s Ability to Define Issues of Social Justice” yang menjelaskan bagaimana budaya pengenyahan dapat secara terstruktur menyerang individu yang melanggar sesuatu di luar norma masyarakat umum dalam platform Twitter. Di satu sisi, pengungkapan konflik terkait isu-isu yang dilontarkan dalam media sosial menjadi baik jika itu terkait dengan tuntutan keadilan sosial dan politik, menyerang mereka yang menindas dan terbukti salah melawan konstitusi. Namun, juga tidak banyak publik menggunakan budaya pengenyahan ini sebagai alasan untuk membesarkan drama kecil hingga cara untuk membangkitkan gosip dibanding mempromosikan keadilan sosial (Wiseman, 2021). Dalam hal ini, platform Twitter menjadi ruang bebas yang cenderung lebih mudah untuk ikut membungkan target pengenyahan.
Twitter sebagai Ruang Bola Api Liar Budaya Pengenyahan
Twitter memiliki potensi untuk memungkinkan suara-suara yang sebelumnya tidak memiliki platform, dapat berbicara, didengar, berkumpul, berbagi ide dan minat, dan memobilisasi. Namun, terdapat elemen lain yang membentuk kredibilitas sumber informasi di Twitter yang cenderung subjektif, yaitu hubungan antara pembuat konten dan individu. Misalnya, pengguna lebih cenderung menganggap tweet sebagai sesuatu yang kredibel jika berasal dari sumber yang lebih dekat dengan mereka, seperti teman atau akun yang telah diikuti oleh pengguna. Hal ini juga menimbulkan kerancuan dalam informasi ketika Twitter dianggap sebagai News Media.
Platform Twitter juga memiliki kuasa terhadap bagaimana opini publik dibentuk dan berdampak pada korban dari budaya pengenyahan. Seperti studi Lopez & Budaj (2021)“Tug of War: Social Media, Cancel Culture, and Diversity for Girls and The 100”, bahwa tagar dari budaya pengenyahan bisa menjadi viral, menghasilkan petisi online atau gerakan yang menyerukan industri hiburan untuk membuat perubahan drastis. Dan pada akhirnya, industri hiburan sebagai bisnis berusaha untuk membuat penggemar (alias pelanggan) senang dan mempertahankannya. Meskipun hal ini berujung pada putusnya kontrak atau hilangnya kesempatan pekerjaan bagi seseorang yang ditargetkan.
Dari berbagai studi yang telah dilakukan sebelumnya, budaya pengenyahan telah dilihat dari dua sisi yang berbeda. Sisi pertama, dari sisi positif yang disebut sebagai pengungkapan suara-suara yang minor. Melalui platform sosial media seperti Twitter, gerakan tagar-tagar terbukti berhasil memobilisi gerakan aktivisme digital. Meskipun, studi Butler (2011) “Clicktivism, Slacktivism, or “Real” Activism? Cultural Codes of American Activism in the Internet Era” menemukan adanya istilah slacktivism yang melekat pada cancel culture di mana publik yang berpartisipasi dalam gerakan tagar tertentu tidak seutuhnya berpartisipasi, hanya pada gerakan-gerakan semu dengan mengandalkan like, retweet, komen, dan petisi. Alih-alih berkomentar secara obektif, publik hanya ikut meramaikan cuitan dengan perundungan terhadap target cancelled.
Di sisi kedua, budaya pengenyahan lebih membahayakan. Perang budaya adalah tentang kontrol naratif, siapa pun yang dapat membentuk atau memengaruhi wacana saat ini memiliki kemampuan untuk mengarahkan opini publik secara masif. Selain tidak hanya berdampak pada rusaknya citra seseorang, lebih dari itu, budaya pengenyahan seolah-olah membungkam suara-suara para target cancelled di ruang publik yang seharusnya menjadi hak setiap individu.
Setelah melihat dari kedua sisi, kita dapat melihat bahwa budaya pengenyahan tetap akan menjadi ekosistem dalam budaya siber dan tetap akan menjadi pisau bermata dua dan bola api liar dalam kaitannya dengan kebebasan bersuara di ranah virtual. Pertanyaannya, masihkah kita meyakini apa itu kebebasan dalam ruang-ruang yang seharusnya memfasilitasi kita untuk tetap menjadi bebas dalam bersuara?
Referensi
_(2021, June 25) Gofar Hilman Kembali ke Dunia Maya dengan Video Perkembangan Kasusnya. Diakses dari https://www.pramborsfm.com/news/gofar-hilman-kembali-ke-dunia-maya-dengan-video-perkembangan-kasusnya
Anderson-Lopez, J., Lambert, R. J., & Budaj, A. (2021). Tug of war: Social media, cancel culture, and diversity for girls and the 100. KOME, 9(1), 64–84. https://doi.org/10.17646/KOME.75672.59
Aviles G (2019, December 20) J.K. Rowling faces backlash after tweeting support for ‘transphobic’ researcher. Diakses dari https://www.nbcnews.com/feature/nbc-out/j-k-rowling-faces-backlash-after-tweeting-support-transphobic-researcher-n1104971
Bouvier, G. (2020). Racist call-outs and cancel culture on Twitter: The limitations of the platform’s ability to define issues of social justice. Discourse, Context and Media, 38. https://doi.org/10.1016/j.dcm.2020.100431
Butler, M. (2011). Clicktivism, Slacktivism, or “Real” Activism? Cultural Codes of American Activism in the Internet Era. https://scholar.colorado.edu/comm_gradetdshttps://scholar.colorado.edu/comm_gradetds/12
Gibson, K (2020, July 09) Florida insurance agent fired after mask meltdown at Costco. Diakses dari https://www.cbsnews.com/news/costco-dan-maples-face-mask-fired-insurance-agency-florida/
Ndn, wis (2020, Agustus 12) Jerinx Dijerat Pasal SARA, Pengacara Sebut IDI Ikatan Profesi. Diakses dari https://www.cnnindonesia.com/nasional/20200812194733-12-535091/jerinx-dijerat-pasal-sara-pengacara-sebut-idi-ikatan-profesi
Noelle‐Neumann, E. (1974). The spiral of silence a theory of public opinion. Journal of communication, 24(2), 43-51.
Sailofsky, D. (2021). Masculinity, cancel culture and woke capitalism: Exploring Twitter response to Brendan Leipsic’s leaked conversation. International Review for the Sociology of Sport. https://doi.org/10.1177/10126902211039768
Saint-Louis, H. (2021). Understanding cancel culture: Normative and unequal sanctioning. First Monday, 26(7). https://doi.org/10.5210/fm.v26i7.10891
Wiseman, E. (2021). This article is more than 11 months old Is it time we cancelled cancel culture?. Theguardian.com. Diakses dari https://www.theguardian.com/lifeandstyle/2021/dec/05/is-it-time-we-cancelled-cancel-culture
.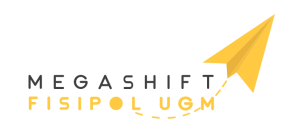






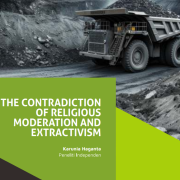



Leave a Reply
Want to join the discussion?Feel free to contribute!