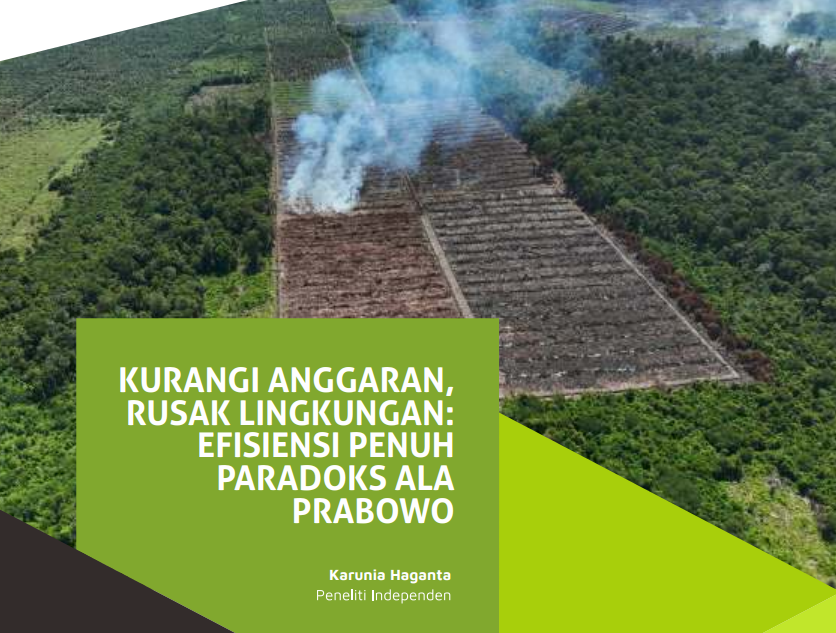Awal 2025, pemerintahan baru Prabowo Subianto telah membuat gebrakan baru dengan melakukan pemotongan anggaran besar-besaran. Kebijakan yang disebutnya “efisiensi” ini secara masif mengurangi anggaran berbagai lembaga negara yang dianggap pemborosan. Banyak yang mengeluhkan dampak langsung efisiensi ini, mulai dari pemecatan terhadap banyak tenaga honorer yang kerap berada di garis depan pelayanan, penurunan fasilitas kerja, sampai ancaman dihentikannya program-program bantuan pendidikan.
Namun, kritik terbesar bagi efisiensi ini sesungguhnya adalah kontradiksi pemerintahan Prabowo. Sejak awal, Prabowo membentuk kabinet yang dianggap tidak proporsional dengan banyaknya posisi dan jabatan yang diberikan (Sood, 2024). Kontradiksi ini makin terlihat dengan rencana Prabowo untuk mengalihkan dana pada program kontroversial Makan Bergizi Gratis (MBG), dan yang terbaru adalah lembaga kontroversial Danantara (Siswanto, 2025).