Wisata Seks Online dan Implikasinya Terhadap Pekerja Seks: Kajian Pariwisata & Rekreasi
Beberapa negara telah melegalkan wisata seks karena keuntungan yang diperoleh, di sisi lain, banyak negara melarang bisnis ini karena salah satu bentuk kejahatan hak asasi manusia paling buruk (Leung, 2015: 83). Masalahnya, teknologi informasi dan komunikasi (TIK) digunakan untuk mempromosikan bisnis ini, sementara pekerja seks memindahkan bisnisnya secara digital. Fenomena tersebut membuat pekerja seks menjadi rentan terhadap tindakan kejahatan seksual, apalagi bisnis wisata seks sering melibatkan anak dibawah umur untuk diperdagangkan secara seksual (Jeffreys, 2010: 185). Dengan demikian, tulisan ini menjelaskan perubahan aktivitas industri wisata seks akibat disrupsi teknologi.
Wisata seks adalah perilaku terencana melakukan perjalanan dengan tujuan melakukan kegiatan seks (Blackburn, Taylor, & Davis, 2011: 122). Carr (2016: 2) mengatakan seks adalah konstruksi kesenangan dan hiburan manusia yang bisa memotivasi mereka untuk berwisata. Banyak negara mengandalkan bisnis wisata seks karena menguntungkan dan meningkatkan pendapatan (Bishop & Robinson, 1998: 88). Negara yang mengizinkan wisata seks mendapatkan keuntungan tidak sebatas pada pertukaran uang, melainkan perusahaan maskapai penerbangan, akomodasi, fasilitas hiburan dan agen perjalanan juga mendapatkan keuntungan cukup besar (Bunn, 2010: 17). Di Thailand, bisnis wisata seks menyumbang 10 persen atau US$ 6,4 miliar dari seluruh produk domestik bruto (Boccagno, 2015). Kegiatan seks tradisional dilakukan di fasilitas khusus yang disediakan negara seperti akomodasi, klub malam dan distrik. Kegiatan seks antara pekerja dengan wisatawan akan diatur oleh individu yang mengelola tempat rekreasi (Bauer, McKercher, 2003).
Destinasi wisata seks yang terkenal adalah wilayah red light district di De Wallen, Amsterdam, Belanda. Wilayah tersebut menjadi tempat aman dan legal pekerja seks memperoleh keuntungan sekaligus tempat ikonik yang dikunjungi banyak wisatawan (Nugent, 30 Oktober 2019). Filipina di Kota Angeles juga menjadi wilayah khusus untuk wisatawan melakukan kegiatan seks dengan ratusan bar dan hotel (Jeffreys, 2010: 191). Wisatawan yang ingin menghilangkan rasa kesepian dengan melakukan kegiatan seks juga dapat berkunjung ke Thailand yang menyediakan banyak tempat bar, tempat pijat, diskotik dan rumah bordil (Yokota, 2007: 117). End Child Prostitution in Asian Tourism (ECPAT) tahun 2016 memperlihatkan tujuh wilayah Indonesia yang menjadi destinasi wisata seks, seperti Yogyakarta, Bali dan Nusa Tenggara Barat. Bisnis wisata seks telah terindustrialisasi dan terglobalisasi sehingga menjadi lebih besar. Distrik prostitusi tidak hanya memfasilitasi kebutuhan seks semata, melainkan menyediakan berbagai bentuk rekreasi lainnya seperti kasino. Sementara itu, perdagangan seks manusia juga semakin tinggi karena tingginya permintaan melakukan seks. Mereka diperdagangkan biasanya berasal dari negara berkembang kemudian bermigrasi ke negara yang melegalkan wisata seks. (Jeffreys, 2010: 185).
Wisata seks online
Pertumbuhan media digital mentransformasi bisnis wisata seks dan membuat bentuk eksploitasi baru. Pekerjaan yang semula terjadi di red light district, sekarang dilakukan di rumah atau studio pribadi. Teknologi webcamming, instant messaging dan phone call telah menciptakan pekerjaan seks daring (Vlase & Preoteasa, 2021: 2). Pekerja seks daring acapkali menunjukkan diri depan kamera dengan tampil erotis seperti menari menggunakan bikini, mengenakan kostum bahkan telanjang dan menampilkan pertunjukan masturbasi (Gezinski dkk, 2015: 9; Vlase & Preoteasa, 2021: 4). Pekerja seks dapat mendaftarkan diri pada platform digital populer seperti OnlyFans, Chaturbate, LiveJasmin dan MyFreeCams untuk memberikan layanan erotis. Studio pribadi juga menjadi pilihan pekerja seks untuk memproduksi konten pornografi (Pratama, 2023). Website www.slyguide.com dan www.sex-tourism.org diciptakan untuk mempromosikan wisata seks oleh pelanggan (Bunn, 2010: 19), sementara pekerja seks mempromosikan secara pribadi atau melalui jaringan manajemen di media sosial (Shannon dkk, 2014: 2).
Kini, bisnis wisata seks dilakukan terang-terangan di platform digital untuk tujuan finansial dan kesenangan (Jones, 2018: 2). Platform digital menawarkan keberagaman seksualitas daripada pekerjaan seks konvensional. Pekerja seks yang memiliki kulit hitam, badan gemuk dan kategori terpinggirkan lainnya mempunyai tempat di platform digital sebagai pemain seks (Jones, 2018: 5). Pada wisata seks daring, pemain menampilkan adegan erotis tanpa memandang kebangsaan, ras, jenis kelamin, orientasi seksual atau ukuran tubuh. Mereka tidak perlu melakukan hubungan seks dengan pelanggan, melainkan memenuhi permintaan kesenangan dan rangsangan seksual pelanggan. Pemain memiliki kendali atas apa yang direkam dan mengontrol konten pertunjukan. Sementara itu, Platform digital dapat menampung banyak pemain dan memberikan peraturan pertunjukan seperti tidak melibatkan anak-anak dan adegan bestiality (Jones, 2018: 6). Menurut Vlase & Preoteasa (2021: 4) pemain bisa melarang akses penonton berdasarkan internet protocol address yang berdomisili sama dengan mereka agar melindungi privasi. Kegiatan seksual yang dimediasi oleh teknologi menggeser paradigma ekonomi digital dimana tubuh manusia menjadi komoditas untuk memenuhi kesenangan orang lain.
Shimshak (2020: 356) mengatakan pemain yang menampilkan adegan erotis akan memperoleh respon positif penonton seperti peningkatan jumlah hadiah. Jean-Francois Lyotard (1974: 2-76) mengatakan seluruh tubuh manusia (libidinal) adalah komoditas yang digunakan sebagai alat tukar (libidinal currency). Implikasi model perekonomian seperti itu adalah banyak individu berpartisipasi dalam pertunjukan erotis demi kepuasan orang lain yang kemudian mendapatkan keuntungan dari platform streaming melalui hadiah digital (Shimshak, 2020: 357). Gesselman dkk (2022) mengatakan orang dewasa sering terlibat aktivitas seksual yang dimediasi teknologi. Fenomena tersebut dimanfaatkan oleh industri digital mengeksploitasi tubuh untuk mendapatkan keuntungan atau dikenal platformisasi pekerja. Pekerja seks mendapat keuntungan berdasarkan durasi streaming dan peringkat (algoritma) platform yang digunakan. Vlase & Preoteasa (2021: 4) mengatakan peringkat dibuat secara subjektif dengan mengandalkan nilai dominan seperti ras, tinggi badan, berat badan, warna kulit dan sebagainya. Pekerja seks daring sering bekerja lebih keras dan lama untuk mendapatkan keuntungan yang lebih banyak. Mereka juga harus menerima reduksi keuntungan dari platform dan memerlukan peralatan canggih untuk menunjang performa mereka.
Walaupun pekerja seks menjadi aktor, produser dan sutradara pada kegiatan seks daring, mereka tidak mempunyai kekuatan sistem algoritma dan penyimpanan data platform digital pornografi dibuat. Menurut Tziallas (2018) individu diawasi oleh segala sesuatu tentang porno yang dapat mengendalikannya (pornopticon). Penonton yang memiliki kewarganegaraan sama dapat menggunakan jaringan pribadi virtual untuk menonton adegan erotis, sementara data pribadi di platform digital juga mudah diretas oleh orang lain, kemudian dicuri dan disebarkan di internet tanpa persetujuan pemilik (Tziallas, 2018; 3; Chan, 2018: 2). Pekerja seks online sangat rentan terhadap tatapan pria yang dimediasi teknologi kamera. Tatapan pria menjadi pengawas yang menyebabkan kekerasan seksual. Menurut Vlase & Preoteasa (2021: 7) pekerja seks wanita sering mendapatkan diskriminasi dibandingkan pria. Faktanya, ada banyak potongan pornografi perempuan yang muncul di internet. Identitas pekerja seks yang terbongkar cenderung ditolak masyarakat sehingga sulit untuk memenuhi kebutuhan sosial.
Kelompok yang setuju terhadap wisata seks berargumen bahwa seks adalah kebutuhan fisiologis manusia yang perlu dipenuhi. Mereka juga menganggap wisata seks sebagai bentuk pariwisata rekreasi dan pekerjaan yang sah, membutuhkan kemampuan khusus dan sebagai pilihan individu (Jeffreys, 2010: 179-180). Negara Inggris, Amerika Serikat, Belanda dan negara lain melegalkan bisnis tersebut dengan mengatur secara ketat kegiatan seks tradisional maupun daring. Misalnya, Negara Inggris yang mengatur hak cipta dan paten konten pornografi sebagai bentuk karya (Bak & Nocella, 2023: 438). Namun, Broadhurst (2020: 315) mengatakan individu terlibat dalam wisata seks karena perekonomian buruk dan hidup di wilayah tertinggal. Banyak feminisme menentang bisnis ini karena alasan kemiskinan dan dianggap tidak memerlukan kemampuan, melainkan hanya menampilkan tubuh sebagai bentuk eksploitasi (Jeffreys, 2010: 180).
Tantangan ke depan
Pekerja seks daring dapat dikategorikan sebagai pekerja gig atau pekerja yang tidak mempunyai kontrak tetap, namun memperoleh pendapatan melalui pertunjukan yang ditampilkan di platform digital. Mereka adalah pekerja rentan karena negara kurang mampu memberdayakan dari aspek pekerjaan, perlindungan keselamatan dan kesehatan. Dengan demikian, negara yang membiarkan dan tidak memedulikan aktivitas pekerja gig menjual konten bagian tubuh intim untuk mencari dukungan ekonomi perlu mulai mengakomodasi mereka. Negara perlu membuat perlindungan hukum bagi pekerja gig seperti perlindungan keselamatan dan kesehatan, peraturan waktu kerja dan hak upah minimum karena mereka memiliki hak atas karya mereka dan sering mendapatkan kecaman. Sementara itu, perlindungan data pribadi pekerja seks juga penting sehingga sosialisasi perilaku berinternet aman sangat perlu dilakukan sebagai strategi intervensi.
Referensi
Bak, B., & Nocella, R. R. (2023). Unveiling Copyright Law Double Bind Through Pragmatist Feminism: Adult Content Creators as Authors, Porn Studies, 10:4, 431-451, 10.1080/23268743.2023.2225531.
Bauer, T. G., & McKercher, B. (2003). Sex and Tourism: Journeys of Romance, Love, and Lust. New York: The Haworth Press.
Bishop, R. & Robinson, L. (1998). Night Market: Sexual Cultures and the Thai Economic Miracle. New York: Routledge.
Blackburn, A., Taylor, R., & Davis, J. (2011). Understanding the Complexities of Human Trafficking and Child Sexual Exploitation: The Case of Southeast Asia. In F. Bernat (Ed.), Human sex trafficking (pp. 104–125). London: Routledge.
Boccagno, J. (2015). Thailand: Empower, Don’t Pity, the Trans Sex Worker. Retrieved from https://pulitzercenter.org/stories/thailand-empower-dont-pity-trans-sex-worker.
Broadhurst, R. (2020). Child Sex Abuse Images and Exploitation Materials. In Leukfeldt & Holt. The Human Factor of Cybercrime. New York: Routledge.
Bunn, D. (2011). The Economic Impact of Prostitution in the Tourism Industry with a Focus on Sex Tourism in Asia. In Alexis Papathanassis (Ed.). The Long Tail of Tourism: Holiday Niches and their Impact on Mainstream Tourism. Gabler Verlag: Jerman.
Carr, N. (2016). Sex in Tourism: Reflections and Potential Future Research Directions. Tourism Recreation Research, 41: 2, http://dx.doi.org/10.1080/02508281.2016.1168566.
Chan, J. (2018). Violence or Pleasure? Surveillance and the (Non-)consensual Upskirt. Porn Studies, 5:3, 351-355, 10.1080/23268743.2018.1472035.
ECPAT (2016). Indonesia Salah Satu Tujuan Wisata Seks. Retrieved from https://ecpatindonesia.org/berita/indonesia-salah-satu-tujuan-wisata-seks/.
Gesselman, A. N., Kaufman, E. M., Marcotte, A. S., Reynolds, T. A., & Garcia, J. R. (2023). Engagement with Emerging Forms of Sextech: Demographic Correlates from a National Sample of Adults in the United States. The Journal of Sex Research, 60:2, 177-189, 10.1080/00224499.2021.2007521.
Gezinski, L. B., Karandikar, S., Levitt, A., Ghaffarian, R. (2016). ‘Total Girlfriend Experience’: Examining Marketplace Mythologies on Sex tourism Websites. Culture, Health & Sexuality. An International Journal for Research Intervention Care. 18: 7, http://dx.doi.org/10.1080/13691058.2015.1124457.
Jeffreys, S. (2010). Globalizing Sexual Exploitation: Sex Tourism and Traffic in Women. Leisure Studies, 18: 3, 179-196. http://dx.doi.org/10.1080/026143699374916.
Jones, A. (2019). The Pleasures of Fetishization: BBW Erotic Webcam Performers, Empowerment, and Pleasure. Fat Studies, 8:3, 279-298, 10.1080/21604851.2019.1551697.
Leung, P. (2015). Child Sex Tourism. Tourism Recreation Research, 28: 2, 83-87. http://dx.doi.org/10.1080/02508281.2003.11081407.
Lyotard, J. (1974). The Great Ephemeral Skin & The Tensor. In lain Hamilton Grant (Trans). Libidinal Economy. The Athlone Press: London.
Nugent, C. (2019). Amsterdam’s Red Light District Is in Crisis. Can the City’s First Female Mayor Remake It for the 21st Century? Retrivied from https://time.com/5712420/amsterdam-red-light-district-change/.
Pratama (2023). Menguak Skandal Produksi Film Porno yang Melibatkan Para Pesohor. Retrieved from https://tirto.id/menguak-skandal-produksi-film-porno-yang-melibatkan-para-pesohor-gP3k.
Shannon, K. et al. (2014). Global Epidemiology of HIV among Female Sex Workers: Influence of Structural Determinants. The Lancet, 385: 9962, https://doi.org/10.1016/S0140-6736(14)60931-4.
Shimshak, A. K. (2020). Livestreaming: The Mainstreaming of the Commodified Body and Sexual Labor in Thailand. Asian Journal of Women’s Studies, 26:3, 347-364, 10.1080/12259276.2020.1818929.
Tziallas, E. (2018). The Pornopticon. Porn Studies, 5:3, 333-337, 10.1080/23268743.2018.1481766.
Yokota, F. (2007). Sex Behavior of Male Japanese Tourists in Bangkok, Thailand. Culture, Health & Sexuality. An International Journal for Research Intervention Care, 8: 2, 115-131, http://dx.doi.org/10.1080/13691050500526068.
.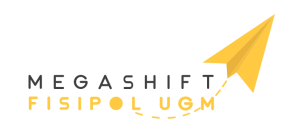
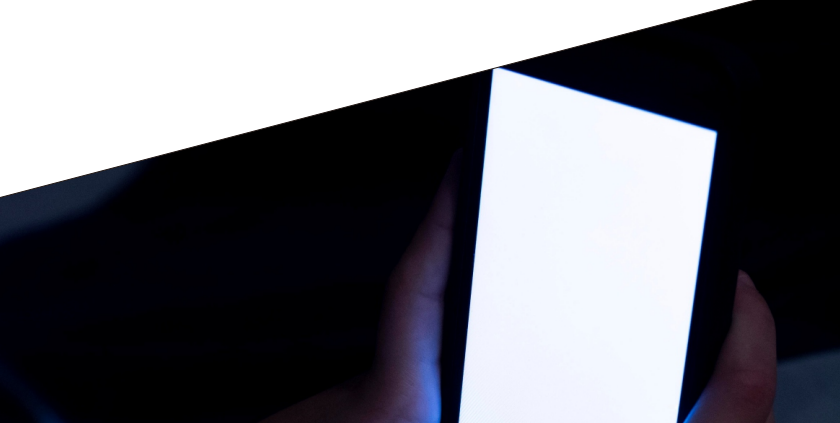









Leave a Reply
Want to join the discussion?Feel free to contribute!